(Yes, this is not a trick post because I am actually uploading a content here after a while. Bahasa Indonesia alert!)
Ini mungkin review film paling gercepku, yang didasari oleh hasil ngide dadakan bersama sesosok manusia laki-laki (we’re not romantically related, BTW. But still, I’m not going to mention his name and I’m going to refer to him as `dia` to respect our privacy). Berawal dari kemarin malem aku tanya, mau nonton apa nggak (tujuan awal kita jalan itu… belanja. Iya. Belanja) berhubung aku tertarik nonton Five Feet Apart. Cole Sprouse yang berperan sebagai male lead-nya, and that’s the selling point… at least to me. Bebas, katanya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba pindah haluan ke Captain Marvel. Tapi kemudian dia bilang kalau film Marvel itu lebih seru kalau ditonton rame-rame. Nggak salah sih. Ya udah, pindah haluan. Jadilah, kita akhirnya memutuskan untuk balik ke film pertama yang disebut dalam ruang chat kita: Five Feet Apart.
Sesampainya di bioskop, beli tiket, makan kilat sampe kenyang parah (korban promo, maklum, dua-duanya anak rantau), terus ngobrol sebentar sebelum masuk ke studio. Dia bilang Five Feet Apart bagus. Ternyata dia udah baca review dong, guys. Sementara aku langsung sosor aja milih Five Feet Apart karena Cole Sprouse. HAHAHA sampis emang. Kita berdua sih udah expect, yah, the kind of chic-flick your boyfriend is willing to watch only because you wanted to watch it so bad. Tearjerker sejenis Me Before You dan If I Stay. Jadi kita udah bersiap-siap menerima segala macam dialog dan adegan klise. Bahkan aku udah bawa tissue dan kasih dia ultimatum berbunyi, “Pokoknya kalau aku nangis jangan diketawain ya.”
(Yang sialnya, dijawab, “Santai lah. Paling cuma gua hujat.” sambil cengengesan ga jelas.)
Sedikit side note, kita berdua tipe orang yang kalau nonton ya, diem. Anteng. Ga neko-neko. Nikmatin aja filmnya sampai habis. Minim komentar. Seriusan, dalam waktu 2 jam 15 menit itu mungkin kita cuma 2-3 kali bertukar kata. Topik pertama dimulai dengan protesku tentang ketidakcocokan rating dengan satu adegan. Sebenernya cocok sih, cuma menurutku innuendo-nya untuk standar rating PG-13 di Indonesia cukup kuat. Takutnya nanti ada mamak-mamak yang bawa anaknya marah-marah, ya kan.
Terus, topik kedua. Dia sempet ngecek apakah aku nangis. Haha. Sayang sekali, Ferguso, aku cuma mewek kok waktu itu. Setelah beberapa menit lewat, tibalah adegan klimaks dari film yang kita tonton. I thought I heard a sob, but it was awfully faint. Namanya Chella, anaknya sering penasaran, nolehlah ke dia.
Dia. Nangis.
‘Ya Tuhan, temanku ternyata adalah seorang big softie,’ batinku. Antara gemes, pengen ngetawain sambil ngehujat, atau ikutan nangis. Dan ya, dari pengantar singkat ini, bisa dikonklusikan se-bikin-mewek-apa film ini, walaupun yang nonton sesama feeler beda gender.
Kayak biasa, aku bakal ngupas dari berbagai segi dengan spoiler seminim mungkin. Kalau mau spoiler-free, boleh banget tekan tombol Back. Tapi kalau mau lanjut baca, dipersilakan. Maaf ya kalau aku merusak momen nonton kalian atau gimana. Hehe. Inget, udah diingetin dari awal ya.
Cast
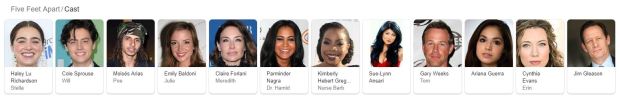
Courtesy of Google
A little intro first. Cerita ini berfokus pada seorang gadis yang mengidap cystic fibrosis (CF) bernama Stella. Stella cinta mati sama yang namanya keteraturan. Dia nggak bisa nggak mengorganisir dan menata semuanya agar teratur. Sedangkan karakter kedua, Will Newman, bersanding kontras sama Stella. Will sama-sama mengidap CF tapi dibonusin dengan bakteri B. Cepacia. Hanya saja, pendekatan mereka terhadap penyakit yang tumbuh dalam diri mereka bener-bener beda. Stella berjuang sekeras mungkin untuk tetap bertahan hidup, sementara Will? Semacam penganut prinsip You Only Live Once. I don’t know if it’s only me, tapi entah kenapa, image seorang Jughead Jones yang misunderstood emo-ish rebel melekat banget di karakter Will.
Buat yang dulu ngikutin Hannah Montana, pasti ada nama yang familiar di deretan aktor-aktris yang main di Five Feet Apart–yes! It’s Moises Arias! Rasanya nostalgia banget ngeliat dia di layar, membawakan segala ke-sassy-annya dalam karakter Poe, sahabat baik Stella. Ada juga perawat bernama Barbara yang strict bukan main, tapi peduli banget dengan remaja-remaja yang dirawatnya.

Find this line: “Don’t even think about it, hoe.”
Anyways, dari segi karakter dan pemeran, aku suka. Banget. Perkembangan karakternya terasa banget. Terlepas dari kekhasan aktor/aktris, karakterisasi mereka kuat banget dan emosinya, beuh. Bukan main. Spent the last half of the movie awed by how the talents (writers, actors/actresses, videographer) managed to pull out almost every characters’ vulnerability without ruining or drifting apart from the main plot.
Plot & Storyline
Masukkan keterangan di sini: Chella yang sedang tidak tahu mau bilang plotnya pasaran atau tidak.
Sungguh. Ini keputusan yang sulit sih. Di satu sisi, aku nahan ketawa dan angguk-angguk aja waktu ada adegan atau kalimat yang kejunya minta ampun. Tapi di sisi lain, menurutku banyak yang tidak terduga. Contohnya, asumsiku bakal ada kematian yang ditargetkan pada karakter tertentu, tapi setelah filmnya berakhir, you would not have any single bloody idea whether there is an existence of death in that movie or not.
Inti hubungan dari Will sama Stella sudah jelas lah ya, mau dibawa kemana. Tapi ada satu catatan dari aku, sih: kenapa awalannya kayak gitu? Aku nggak berharap lebih romantis, nggak. Tapi buat aku, fase pertama mereka bertemu dan kenalan agak seperti diburu-buru durasi. Untungnya, detail minor ini ketutup sama naik turunnya film ini. Aku ga berhenti nonton sama sekali. Rasanya tiap cerita sampingan, bisa melebur tanpa kentara beda. Tiap detik nggak ada celah kosong yang terlalu lama sehingga filmnya nggak bikin bosan. Aku salut banget dengan hal ini. Semua orang bisa ngisi 135 menit dengan apa aja, tapi jarang ada yang bisa bikin semuanya padat dan relevan sama keseluruhan plot besarnya.
Puji syukur kepada Yang Di Atas karena akhirnya, penyakit yang dibawa masuk ke cerita bukan kanker. Hallelujah. Menurutku, kanker itu kelewat overrated di budaya pop sinematik dan teks. Rasanya kanker lagi, kanker lagi. Awareness untuk penyakit lain kemana? Orang jadi masa bodoh sih sama CF kalau film ini nggak angkat. For real, aku bahkan nggak tahu apa-apa tentang CF sampai aku nonton film ini. Tapi mohon maaf, untuk aspek medical accuracy yang merinci, aku bungkam deh. Bagi mahasiswa/i FK, waktu dan tempat dipersilakan.
Oh! Dan dua kata yang akan buat kalian baper: tongkat billiard. Benda ini sakral. Jadi andil utama tajuk film ini. HAHAHA. Ditonton aja dulu biar ngerti.
Technicalities
Secara keseluruhan–pengambilan gambar, warna, mood, semuanya dapet. Gerak kamera mulus dan berkesinambungan, bersahabat di mata walau (sepertinya) nggak pake teknik yang kompleks banget. Tone dan key colour-nya didominasi putih dan menjurus ke keluarga warna adem (most likely karena latarnya di rumah sakit saat musim dingin, sih). Konsisten. Saat di adegan-adegan yang main dengan sisi rentan karakter, emosi dan moodnya dapet.

Wardrobe-wise, I’m crazy for Will’s wardrobe. It’s a lot like Jughead but more refined and casual and less-punk. Wait until you see his mask. Adorable and so Jughead-ish to the extremes.
Overall
Hands down, 8.5/10. Sembilan, kalau aku nggak berusaha nahan senyum aneh waktu ada dialog yang menurutku agak picisan. Sangat worth it. Cocok buat kalian yang mau bermelankolis-ria atau bermenye-menye dengan pasangan HAHAHA. Di sini aku mau bilang, aku jatuh cinta dengan segala plot vulnerability dan arti kata melepaskan yang didefinisikan ulang oleh film ini. OTW jatuh miskin juga karena nekat nonton di hari Minggu. Hehe. Cheers! Jangan lupa bawa tisu ya waktu nonton🖤

